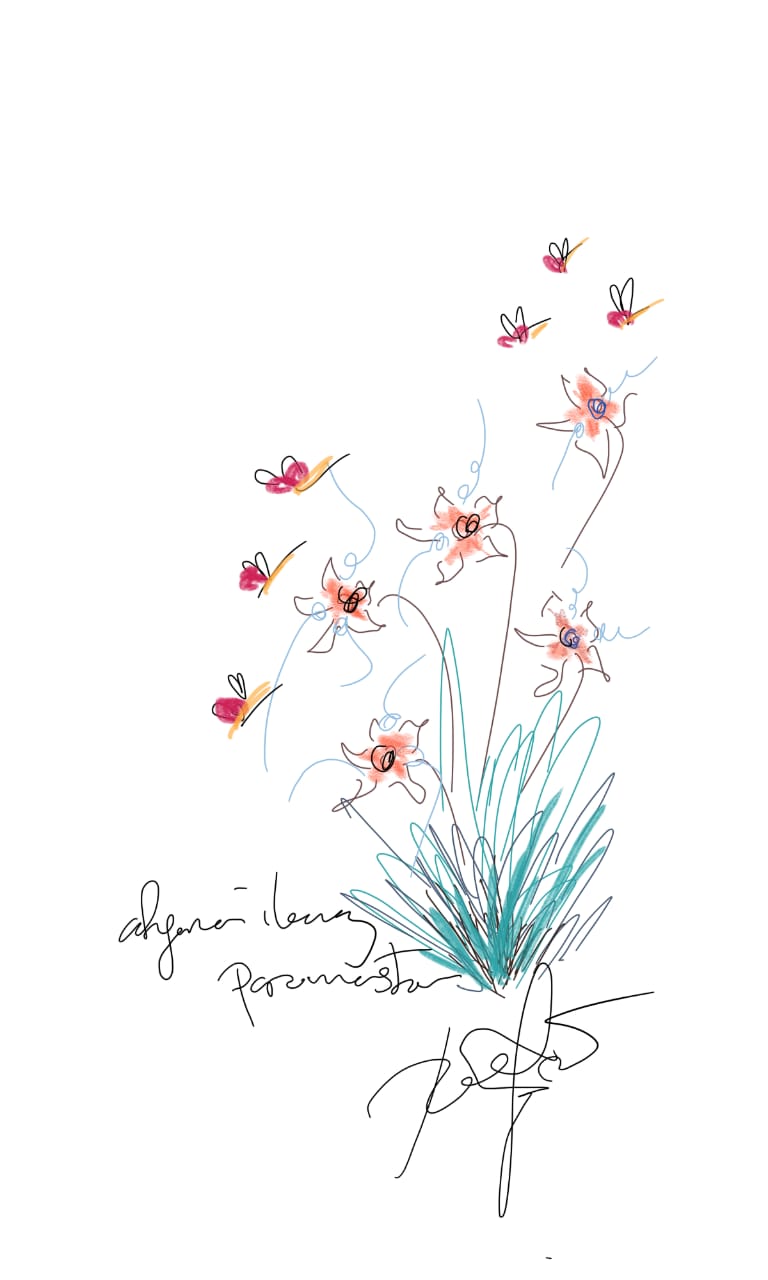
Meretas Jarak
(Otokritik Limangtahunan Sraddha Sala)[1]
Oleh
Rendra
Agusta
Selamat malam kawan-kawan,
Malam ini agaknya saya tidak perlu menyampaikan salam dengan banyak versi, selain bikin repot pastinya juga memperpanjang renungan malam ini. Maka dari itu, sebaiknya saya menyampaikan “selamat malam” saja, semoga semesta dan sesama masih mencintai raga yang didiami jiwa ini. Malam ini ijinkan saya membaca tulisan ini, mengingat saya adalah orang yang imajinatif, agaknya merasa perlu saya membaca tulisan saja, agar renungan menjadi lebih terarah dan terukur. Semoga bisa menjadi bahan perenungan kita bersama, atau setidaknya menjadi dongeng pengantar tidur kawan-kawan yang hadir malam ini.
Paparan ini saya buat persis pada tanggal 2 April, tepat lima tahun yang lalu peringatan seribu hari guru saya, dan agaknya menjadi guru kita semua, Romo I. Kuntara Wiryamartana, S.J. Pada peringatan seribu hari itulah kami membuat komunitas ini.
Saya sering menyebut beliau Romo Kun, beberapa senior dan guru-guru saya menyebut beliau dengan Romo Petruk. Seorang Romo yang membawa Petruk selama menjalani sidang disertasi “Arjunawiwaha”-nya di Leiden. Disertasi yang menjadi jembatan bagi peneliti berikutnya, disertasi yang menjembatani karya sastra pegunungan dan kraton, tentu juga disertasi yang menjembatani kehidupan kita hari ini dengan kehidupan para Ajar di pegunungan di masa lampau.
Romo Kun adalah sosok yang mengubah pandangan akademik saya yang “sangat menara gading” menjadi “pengetahuan untuk masyarakat”. Sebagai murid dari seberang kali Oya, yang harus melewati sungai Gajah Wong untuk sampai di Peguron Sastra tertua di Indonesia (tempat Mas Zaki menjadi guru saat ini), saya menempuh jarak limapuluh kilometer, begitu juga jauhnya jarak pengetahuan saya saat itu tentang Sastra Jawa Kuna. Mungkin jika kami tidak bertemu beliau, saya akan menjadi peneliti sangkar ayam, hidup di dalam kuil-kuil sastra tanpa peduli kanan-kiri dan terus berjarak dengan masyarakat pamengku kebudayaan itu.
Sering saya berceloteh kepada kawan-kawan di kereta Jakarta-Bandung, tentang ucapan Pidi Baiq (Novelis Dilan yang terkenal itu).
“Jangan takut pada jarak, karena jarak hanya nama pohon” – Pidi Baiq
Saya sepakat dengan kata-kata Pidi Baiq ini, tetapi ketakutan pada jarak juga tidak bisa dianggap hal yang remeh begitu saja. Untuk hal-hal sederhana, jarak bisa membuat rindu rindu yang mendalam bagi sepasang sejoli. Tetapi jarak jugalah berpeluang untuk seseorang “mangrwa” – mendua, tumbuh kebosanan, hingga kandasnya sebuah hubungan percintaan. Tentunya malam ini kita tidak hanya akan membincang soal roman picisan dan problematika remaja di era informatika, lebih dari itu kita akan sedikit demi sedikit masuk dalam perbincangan kebudayaan.
Tidak jauh dari dunia roman picisan anak muda, saya pernah mengalami peristiwa menarik ketika saya jatuh cinta dengan seorang perempuan dari tatar sunda. Sebagai seorang keturunan Jawa yang nomaden banyak juga yang menasehati saya. “Jangan nikah dengan orang sunda, nanti bla bla bla” inti nasehat dari teman saya yang orang Jawa adalah menjelekkan orang Sunda. Hal serupa juga terjadi sebaliknya, ketika saya berteman dengan orang Sunda, tak sedikit yang bilang orang Jawa munafik, banyak perbuatan yang berbeda dengan ucapan bla bla bla. Hal yang mencengangkan terjadi ketika saya mengenal beberapa orang dari kedua belah pihak, Jawa dan Sunda, yang mengkukuhkan permusuhan berbasis pengetahuan masa tentang peristiwa Bubat.
“… Tumuli Pasunda Bubat. Bhre Prabhu ayun ing Putri ring Suṇḍa. Patih Maḍu ingutus anguṇḍangeng wong Suṇḍa, ahiděp wong Suṇḍa yan awawarangana …”
“… The start (cause) of Pasunda Bubat. Bhre Prabu who desires the Princess of Sunda sent Patih Madhu, a senior mantri (minister), to invite the Sundanese. Did not mind being a besan (in-law),[iv] came (Prabu Maharaja King of) Sunda (to Majapahit). Instead of being welcomed with a welcoming party, they face the harsh attitude of Mahapatih Gajah Mada who demands the Princess of Sunda as an offering. Sundanese parties disagree and are determined to war.” – Pararaton
Jarak yang jauh antara masyarakat umum dan pengetahuan ini membuat mitos berkepanjangan tentang cerita Bubat. Jarak yang jauh ini akhirnya membuat produksi ulang bacaan-bacaan rakyat dengan berbagai wahana. Hal ini yang menjadi masalah-masalah baru dikemudian hari bahkan masih bisa dirasakan sampai hari ini seperti kisah cinta saya tadi.
Populisme tentang Pa-sunda Bubat mungkin satu fragmen kecil dari masalah bangsa yang tidak tuntas. Di kemudian hari kita masih menemukan Pa-Giyanti, pertarungan budaya yang tidak kunjung selesai sejak 1755. Sambung menyambung tentang narasi nasionalisme yang sempit, dengan ditandai narasi sejarah pada puncak-puncak revolusi hingga isu militeristik dan rasial? Apakah benar ini kebudayaan kita? Jawabannya pasti iya, intrik politik adalah bagian kecil dari kebudayaan kita. Tetapi kalau kita bertanya? Apakah ini peradaban Jawa? Jika peradaban digunakan untuk menata adab manusia agar lebih manusiawi, jawabannya tidak. Kita punya ruang-ruang cinta-cita yang lebih menyejukkan dari sekedar mengurus chauvinisme berbasis teks dan konteks.
Dua tahun yang lalu, saya berkala berkunjung bulanan ke wilayah Kedu sampai Wonosobo untuk mencatat parikan-parikan dalam Lenggeran dan Bundengan. Salah satu lirik yang saya temukan adalah teks Sularsih-Sulanjana. Sebuah anomali, di wilayah Jawa Tengah saya menemukan konteks Sularsih-Sulanjana lebih dikenal daripada Sri-Sadana, lebih dekat dengan kebudayaan tatar Sunda Cirebonan. Tentu saja kisah kelindan kebudayaan antara Sunda-Jawa ini mendasar dan historis dalam teks-teks Jawa Pertengahan, semisal teks Bujangga Manik.
Bujangga Manik merupakan karya sastra
beraksara dan berbahasa Sunda Kuna, hibah Thomas James yang disimpan di Bodlean
Library UK sejak tahun 1627 Masehi. Setidaknya dalam naskah tersebut perjalanan
Bujangga Manik ke Merbabu berhenti di dua tempat yakni Pajaran (Pamrihan,
Mriyan?) dan Pantaran (tempat kita duduk bersama malam ini). Bujangga Manik
belajar bahasa, aksara, ajaran Jawa dengan mengunjungi Ajar-Ajar pegunungan
Jawa.
Kakara cunduk ti gunung, kakara datang ti wetan,
cunduk di gunung Damalung, datangna ti Pamrihan, datang ti lurah pajaran.
Aku baru datang dari gunung, aku baru saja tiba dari timur,
tiba dari gunung Damalung, datang dari Pamrihan, datang dari wilayah aliran agama.
(BM 593-597)
Asak beunang ngajar warah,
asak meunang maca siksa
pageuh beunang maleh pateh
tuhu beunang nu mitutur
asak beunang pangguruan
Matang setelah digembleng,
matang setelah membaca pegangan,
kuat setelah (?) aturan,
setia terhadap apa yang dinasihatkan,
matang
setelah mendapat ajaran.
ti kidul gunung Damalung
inya na lurah Pantaran
di selatan adalah Gunung Damalung,
termasuk ke daerah Pantaran,
(BJ
770)
Petikan ini memberi narasi lain tentang hubungan Sunda-Jawa yang lebih harmonis. Begitu juga malam ini, komunitas memilih Pantaran sebagai ruang renung untuk mengenang keberadaan gunung di depan kita ini. Malam ini kita sangat dekat dengan Merbabu, tetapi apakah benar kita benar-benar mengenal Merbabu sebagai Puja Mandala? Sebagai Sastra Mandala?
Relasi antar Pangajaran antar gunung juga bisa ditemukan dalam Suluk Tambang Raras. Jayengresmi melakukan pengembaraan ke ujung Jawa bagian Barat, berguru pada orang-orang suci di pegunungan, sampai menetap di gunung Karang. Ia mendalami ilmu keislaman bersama Syaikh Karang, setelah dianggap cukup, ia berganti nama menjadi Syaikh Amongraga. Pengembaraaan orang-orang antar pengajaran abad XV-XVII menjadi salah satu prototype yang menginspirasi komunitas ini sejak dari pendiriannya. Pertanyaannya apakah kita dari semua yang hadir ini, mengenal dengan baik masyarakat pegunungan? Kebudayaan yang lahir di dalamnya? Atau ruang-ruang esoteris dalam Wanasrama yang ditinggalkan? Bahkan perubahan kebudayaan dan keagamaan di pegunungan yang lekat dengan hal-hal sosio-ekonomi kadang kita tidak tahu menahu?
Dalam babad pasranggrahan Madusita, satu dari belasan Pasanggrahan yang didirikan kraton Surakarta. Di balik cerita kemegahan kunjungan Sunan, tentu yang tidak tercatat adalah kehidupan masyarakat desa sehari-hari. Kehidupan masyarakat yang harmonis di dalam tekanan “culture stelsel”. Faktanya memang benar wilayah Vorstenlanden ini tidak ada tanam paksa, tetapi para pangeran menyewakan tanah kepada expatriate untuk penanaman tanaman komoditi sejenis, memberi gaji kepada masyarakatnya. Tentu perlu kita renungkan kembali definisi “culture stelsel”, tidak sesederhana tanam paksa, tetapi dengan melihat apa yang ditanam, sistem kerja, sistem penggajian, akan berdampak kepada masyarakat, lagi lagi memunculkan kebudayaan baru. Yang menyesuaikan diri, dia akan selamat, sedangkan yang lainnya akan hilang tergilas arus zaman.
Sesungguhnya hari ini pun kita mengalami hal yang sama. Sebelum pandemi ruang-ruang gerak masyarakat teratur dan diatur dalam sistem kebudayaan besar. Kebudayaan ini bermuara kepada hal-hal besar juga, pada bidang material praktis kita berpacu dalam sosio-ekonomi, sedangkan bidang i-material kita berpacu pada bidang religio-mistika. Dua hal yang agaknya hari-hari ini menjadi jalur besar, dan kadang-kadang mewarnai bidang-bidang lain seperti politik, pangan, kesenian, dan pendidikan.
Pendidikan Indonesia sejak dilengserkannya Ki Hajar Dewantara dari Menteri Pendidikan, sebenernya kita mengacu pada sistem pendidikan gaya Landa. Berseragam, penuh doktrin, diarahkan pada hal-hal material, dll. Hal ini juga merambah ke dunia perguruan tinggi, keberadaan AI, sistem-sistem penangkap plagiasi seperti Ratmin dan kawan-kawannya. Saya masih teringat pidato Mas Pujo Semedi beberapa waktu lalu saat peringatan Dies Natalies Fakultas Ilmu Budaya UGM, “Mari kembalikan kecerdasan akademik kepada akademisinya, bukan pada kecerdasan buatan.” Jika hal ini tetap berlangsung mungkin ilmu budaya tetap ada, ilmu humaniora tetap ada, tetapi sarjana humaniora ini akan semakin jauh dari kemanusiaan itu sendiri.
Secara khusus, dalam bidang pendidikan yang kami geluti, Filologi berkembang begitu pesat, mulai dari digitalisasi naskah, dating karbon, pengembangan font aksara nusantara, tampilan-tampilan tiga dimensi yang serba canggih. Komunitas ini hanya mengambil peran kecil dari perkembangan digital itu, yakni membawa pulang pengetahuan naskah-naskah kepada masyarakat pamengkunya. Secara luas membawa “ilmu humaniora” kembali kepada masyarakat pamengkunya. Mungkin ini dianggap kegiatan yang jadul dan kuno, tetapi jalan ini memiliki arti penting untuk meretas jarak pengetahuan. Sekolah formal kini bersaing ketat dengan “Kyai Hologram”, kadang-kadang yang terlupa adalah kesadaran diri akan bijak berdijital. Hal-hal itu yang perlu kita renungkan bersama. Mengapa narasi yang harmonis ini tidak mencapai puncak-puncak peradaban kita? Peradaban yang kita sebut 4.0?
Limatahunan
Sraddha itu berarti keyakinan.
Kira-kira begitulah kata yang paling sederhana untuk menerangkan kelahiran dari komunitas ini. Komunitas Sraddha tidak terlepas dari lalu lalang kawan-kawan yang pernah bertemu Rama Kuntara, ikut diskusi-kelasnya, dan sampai pembacaan karya-karya untuk mengenang kematiannya. Kumpulan geguritan berjudul panglocita merupakan sisi lain dari Romo Kun yang juga memberikan gambaran kehidupan kita. Salah satu geguritan yang sangat menginspirasi saya saat itu adalah Brajangan. Saya dan kawan-kawan seperti Branjangan yang berteduh mencecap air, lalu sekelebat melanjutkan perjalanannya. Saya merasa begitu cepatnya waktu, hingga sekejap saja mencecap ilmu, lalu sekejap itu pula kita akan kembali kepada Hyang, lengkap bersama ilmu yang kita cecap.
Awal-awal perjalanan sunyi ini dilapaskan perpustakaan Kolose Saint Ignasius Yogyakarta dan Pustaka Artati perpustakaan Sanata Dharma. Dua tempat yang menjadi titik temu kawan-kawan yang sempat dan pernah belajar Jawa Kuna di Yogyakarta, ditempat itulah saya bertemu Romo Kun. Di dua tempat itu pula saya mendapatkan istilah ilmu pecothotan, mungkin sejenis jiwa katon yang lahir dalam banyak karya-karya besar, secara khusus Sastra Jawa. Romo Kun dan Ibu Kartika pun seperti Branjangan, sekejap menjadi guru saya, lalu keduanya kapundhut disaat saya baru saja mencecap ilmu dari beliau berdua.
Sepeninggal mereka berdua, saya seperti Ekalawya, lalu timbulah hasrat untuk menghidupkan kembali mereka dalam pembelajaran-pembelajaran alternatif. Tentunya hal ini berlanjut ketika saya bertemu Mbah Mitro, penunggu lontar terakhir Dakan, yang juga menjadi informan banyak peneliti Merapi-Merbabu. Sejak saat itu saya sering bermain ke desa-desa di lereng-lereng gunung, alih-alih lelah dengan dunia perkotaan dan akademis, sebenarnya saya berguru pada orang-orang bijak di pegunungan. Lebih-lebih saat ruwah seperti saat ini, desa-desa di kaki pegunungan masih menyelenggarakan Nyadran untuk mengenang leluhur. Dari perjalanan itu membukakan mata saya tentang jarak pengetahuan ketika lontar-lontar itu dibawa ke Batavia. Masyarakat Merapi-Merbabu tidak banyak lagi yang tahu tentang keberadaan lontar lebih-lebih isi di dalamnya. Jarak masyarakat sangat jauh dengan museum-museum yang ada di Kuthanagara. Dengan keterbatasan pengetahuan saya, sedikit “keyakinan” saya, maka saya nekat membuat ruang mungil ini di Sala.
Tahun-tahun awal tentunya tidak mudah, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Volunteer yang dengan suka-duka tetap meluangkan waktu demi keberlangsungan komunitas ini. Saya tentu tidak bisa untuk tidak menyebut Universitas Sebelas Maret dan Taman Budaya Jawa Tengah yang mengijinkan pemakaian ruangan untuk diskusi rutin. Setelah itu pastinya Museum Radya Pustaka yang hingga saat ini menjadi ruang tetap diskusi Sraddha Sala. Lima tahun banyak kenangan yang tak bisa dilupakan, mulai antusiasime peserta dari seluruh Jawa, bahkan dari semua kampus yang memiki prodi sastra Jawa dan Jawa Kuna (UNS, UGM, UI, UNNES, UDAYANA, dll). Ada seorang perangkat desa dari Pati yang setiap minggu datang ke Solo, ada pula mahasiswa dari Surabaya yang juga demikian. Rasanya, saya harus menaruh hormat kepada kawan-kawan yang berkenan menjadi bagian dari komunitas ini. Selain antusiasisme peserta, tentujuga dukungan baik moral dan material. Saat komunitas berkunjung ke Wonosobo, ada orang bijak yang tiba-tiba membelikan segerobak Mie Ongklok. Begitu juga ketika kami ke Tulungagung, tiba-tiba ada seorang guru yang memberikan kami satu keranjang Jeruk utuh, luar biasa. Tentunya kami tidak bisa menyebut satu demi satu kawan-kawan (baik secara pribadi, kelompok, maupun instansi) yang pernah dan akan mengambil peran dalam program amatir ini.
Kawan-kawan yang berbahagia semoga belum didera kantuk.
Sekedar untuk mengakhiri paparan saya, tentu saya juga tidak hanya akan mengajak kawan-kawan untuk mengenang yang indah-indah dalam kerja budaya amatir ini. Di luar sana, di luar lingkaran kecil kita malam ini, jarak ilmu pengetahuan begitu jauh, dan agaknya kita bersama perlu bergerak bersama-sama.Bekerja sama pribadi lintas pribadi, komunitas, hingga instansi Negara. Kita perlu mengenalkan kembali perangai ilmiah dalam bentuk yang sesederhana mungkin kepada masyarakat, sehingga pseudosains dan populisme tidak makin menggelapkan mata kita.
Fakta dari sejarah kebudayaan harus kita terima dengan hati terbuka. Tentu kita tidak akan mempelajari Majapahit atau Sriwijaya karena kejayaannya saja, tetapi juga mempelajari mengapa kerajaan sebesar itu bisa hancur? Tentu kita juga masih ingat kekuatan Mataram Islam yang menguasai hamper seluruh Jawa, dibalik itu kita juga harus belajar tentang kehancuran-kehancuran yang ada. Secara khusus, kita punya Pangajaran yang hebat sejak abad VII-XVII. Tetapi kita juga perlu berpikir sejenak akan keberadaan sekolah dan universitas di masa kini. Benarkah pendidikan ini adalah hak segala bangsa? Benarkah pendidikan ini memerdekakan? Bukankah kita juga perlu duduk diam sejenak dan terjaga sembari merenungkan bentuk transformasi pengetahuan yang pas untuk segala bangsa. Sudahkah kita berupaya meretas jarak ilmu pengetahuan untuk kemashlatan umat manusia?
Memang jalan ini adalah jalan yang sunyi, jalan iman yang sunyi, jalan sraddha yang sunyi, semoga kita semua diteguhkan.
Bukan tidak mungkin paparan singkat ini hanya akan menjadi tutur lisan bagi setiap yang ada di sini, lalu dituturkan ke sesama kawan dari angkringan ke restoran-restoran. Paparan ini mungkin juga hanya akan disimpan di awan yang diciptakan raksasa-raksasa, yang bisa dibaca oleh setiap makhluk sebelum katastrofi dimulai. Dari itu semua saya masih berharap paparan ini disimpan dalam Rahim Semesta yang energinya bisa dinikmati oleh siapapun nantinya.
Semoga dengan Wungon Lima Tahunan Sraddha Sala ini kita bisa saling asah, asih, dan asih sebagai manusia di Bumi Allah sekaligus Bumi Manusia ini. Akhir kata, mewakili semua Volunteer, saya mohon maaf jika program amatiran ini tidak mampu memuaskan ingin dan angan kawan-kawan semua.
Selamat malam, selamat merenung, selamat berenang dalam renung.
#ayosinaumaneh Matur nuwun.
[1] Disampaikan pada Wungon Sraddha Sala pada 3 April 2021 di Pantaran, Gladhagsari, Boyolali.
